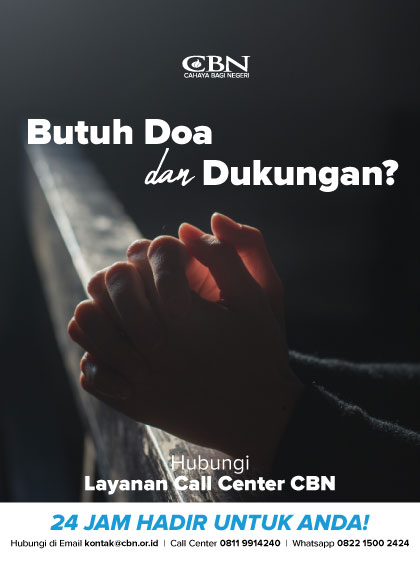Nasional / 21 June 2007
Lingkar Kekerasan Anak Muda

Puji Astuti Official Writer
JAWABAN.com - Realitas kekerasan sosial yang cenderung meningkat di era transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia dipicu oleh meningkatnya sikap dan prilaku intoleransi di kalangan anak muda. Kesimpulan ini diperoleh dari fakta lapangan yang menunjukkan bahwa pelbagai kasus kekerasan sosial sebagian besar dilakukan oleh kalangan muda. Perilaku kekerasan yang dilakukan anak-anak muda ini bisa diklasifikasi dalam tiga bentuk: paramiliter, sektarian, dan teroris.
Bentuk kekerasan anak muda dalam bentuk paramiliter banyak ditemukan dalam pelbagai kasus kekerasan sistematis yang dilakukan oleh organisasi-organisasi massa. Sekitar 80% dari sekitar 1.000 orang yang menyerbu kampus Mubarak Ahmadiyah Parung, Bogor, adalah anak-anak muda, 15 Juli 2005.
Hal yang sama terjadi pada pelbagai penyerbuan dan pengusiran jama'ah Ahmadiyah di pelbagai tempat di Indonesia. Penyerbuan kantor Jaringan Islam Liberal juga dilakukan oleh massa muda, 5 Agustus 2005. Penyegelan dan penutupan gereja-gereja sepanjang tahun 2004 dan 2005 juga dilakukan oleh anak-anak muda dari pelbagai organisasi.
Anak-anak muda yang tergabung dalam massa FPI, FUI, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Hizbut Tahrir Indonesia kembali menunjukkan sikap dan prilaku intoleran ketika mengusir Abdurrahman Wahid (mantan Presiden Republik Indonesia) dari sebuah diskusi lintas iman di Purwakarta, 23 Mei 2006. Massa muda FPI, Forum Betawi Rempug, dan organisasi lain hampir "bentrok" dengan massa Garda Bangsa di Jakarta Utara, Mei 2006. Pelbagai kasus kekerasan lain juga dilakukan oleh anak-anak muda.
Bentuk sektarian ditemukan dalam pelbagai kasus kekerasan di sejumlah daerah. Kekerasan model ini muncul di Poso, Sulawesi Tengah, Ambon, Sambas, Sampit, dan sejumlah daerah lainnya. Pola kekerasan ini muncul dengan penonjolan identitas kultural seperti suku dan agama. Kendati faktor politik dan ekonomi juga sangat besar peranannya sebagai latar belakang, namun ekspresi kekerasan itu ditunjukkan dalam bentuk relasi antariman dan suku.
Individualisme Anak Muda
Terorisme yang marak belakangan ini juga dilakukan oleh sejumlah anak muda. Anak-anak muda itu secara "kreatif" bergerak melampaui batas negara, dan merekrut banyak pemuda dari setiap negara yang mereka "garap". Indonesia adalah salah satu wilayah persemaian terorisme di dunia. Ini terbukti dengan sejumlah kasus terorisme di Indonesia.  Fenomena seperti ini sesungguhnya bukanlah khas Indonesia. Francis Fukuyama dalam The Great Depresión menunjukkan bahwa persoalan besar yang melanda demokrasi Amerika Serikat, Eropa, dan dunia pada umumnya adalah munculnya sikap dan prilaku individualisme yang terlalu tinggi.
Fenomena seperti ini sesungguhnya bukanlah khas Indonesia. Francis Fukuyama dalam The Great Depresión menunjukkan bahwa persoalan besar yang melanda demokrasi Amerika Serikat, Eropa, dan dunia pada umumnya adalah munculnya sikap dan prilaku individualisme yang terlalu tinggi.
Ini bisa menggerogoti rasa saling percaya dan munculnya anarki akibat tiadanya ikatan sosial. Individualisme yang tinggi itu, menurut Fukuyama, marak terjadi di kalangan anak muda Amerika dan Eropa. Anak-anak muda inilah yang menjadi aktor dan pelaku meningkatnya kriminalitas di Amerika dan kerusuhan sosial di Eropa, seperti yang terjadi di Perancis tahun 2005 dan Belanda beberapa tahun sebelumnya. Angka kriminalitas yang terus meningkat tersebut jelas menjadi ancaman besar bagi demokrasi yang justru menghendaki adanya jaminan keamanan dalam mengekspresikan semua kepentingan.
Untuk kasus Indonesia, potensi intoleransi memang sangat mengkhawatirkan.. Hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN, Jaringan Islam Liberal, dan Freedom Institute, November 2004, menunjukkan tingkat sikap intoleransi yang sangat tinggi.
Sekitar 30% responden penelitian ini adalah anak muda, berusia 17 sampai 30 tahun, dan dari kalangan Islam sebesar 87%. Perbandingan laki-laki dan perempuan 50:50. Sebanyak 41,1% responden tidak ingin perempuan jadi presiden; 55% setuju hukum rajam bagi pezinah; 24,8% keberatan jika orang Kristen mengajar di sekolah negeri; 40,8% responden Muslim keberatan jika orang Kristen mengadakan kebaktian di sekitar tempat tinggalnya; dan sebanyak 49,9% keberatan jika orang Kristen membangun tempat ibadah di sekitar tempat tinggalnya.  Angka ini lebih mengejutkan ketika ternyata ada 15,9% responden yang menyatakan dukungan terhadap aksi pengeboman yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawan. Bahkan sekitar 3% mengaku pernah melakukan pemboikotan terhadap barang dan jasa yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Angka ini lebih mengejutkan ketika ternyata ada 15,9% responden yang menyatakan dukungan terhadap aksi pengeboman yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawan. Bahkan sekitar 3% mengaku pernah melakukan pemboikotan terhadap barang dan jasa yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Tiga Penjelasan
Ada tiga penjelasan atas fenomena ini. Pertama, adanya ledakan kelahiran yang terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Angka pertumbuhan masyarakat Indonesia mencapai 1,49% per tahun pada periode 1990-2000, bahkan 1,97% per tahun pada kurun 1980-1990.
Rata-rata penduduk Indonesia bertambah 3 sampai 4 juta jiwa per tahun. Tak ayal, tahun 2000-an memang adalah tahun di mana anak muda begitu dominan. Mereka inilah yang bergerak di tahun 1998 dan meruntuhkan era Orde Baru, tetapi pada saat yang sama, tahun 2000-an, juga bergerak melakukan pelbagai aksi anarkis.
Penjelasan kedua bisa diperoleh dari analisis sosio-politik. Sejak runtuhnya Orde Baru, 1998, sampai sekarang bangsa Indonesia masih berkutat dalam proses pencarian bentuk negara. Jacques Bertrand (Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia), menyebut situasi ini sebagai masa terjadinya "renegosiasi institusional."
Di masa-masa seperti inilah, menurut Bertrand, mobilisasi massa untuk kekerasan sosial gampang tersulut, karena semua orang terpancing untuk bicara tentang negara dan segala perangkat institusionalnya. Pada tataran positif, hal ini mendongkrak angka partisipasi politik, berupa Pemilu, tapi juga bisa berujung negatif pada pelbagai aksi anarkis dan intoleran.
Ketiga, anak-anak muda Indonesia yang ada di pelbagai sekolah menengah dan perguruan tinggi kurang mendapat pengajaran tentang realitas plural masyarakat Indonesia. Yang muncul pada sistem pendidikan Indonesia bukan bagaimana membangun sikap saling menghargai semua perbedaan, melainkan menguatkan identitas secara eksklusif.
Sistem pendidikan inilah yang mengakar kuat di dalam relung kultur anak muda Indonesia. Hal ini diperparah oleh kebijakan umum Orde Baru untuk menabukan perbincangan seputar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).  Menabukan SARA jelas menjadikan sistem toleransi yang dibangun Orde Baru sangat rapuh, sebab yang terjadi adalah adanya sikap saling tertutup antar-identitas, tidak ada upaya untuk saling memahami.
Menabukan SARA jelas menjadikan sistem toleransi yang dibangun Orde Baru sangat rapuh, sebab yang terjadi adalah adanya sikap saling tertutup antar-identitas, tidak ada upaya untuk saling memahami.
Ketika Orde Baru runtuh, masyarakat Indonesia, terutama anak muda, mengalami keterkejutan kultural melihat realitas keragaman, lalu mereka mengambil sikap defensif, menjaga keutuhan identitas sendiri. Akhirnya, yang lain dipandang sebagai ancaman, bukannya sebagai mitra dialog.
Pembangunan kesadaran kultural di kalangan anak muda mengenai keragaman perlu dibangun sejak dini untuk menumbuhkan sikap toleran terhadap yang lain. Dengan inilah rasa saling percaya sebagai modal sosial demokrasi bisa tercipta. Anak muda seharusnya bukan ancaman, melainkan aset yang harus dikembangkan.
*Penulis adalah peneliti Forum Muda Paramadina; Alumnus Teologi dan Filsafat UIN Jakarta.(nat)